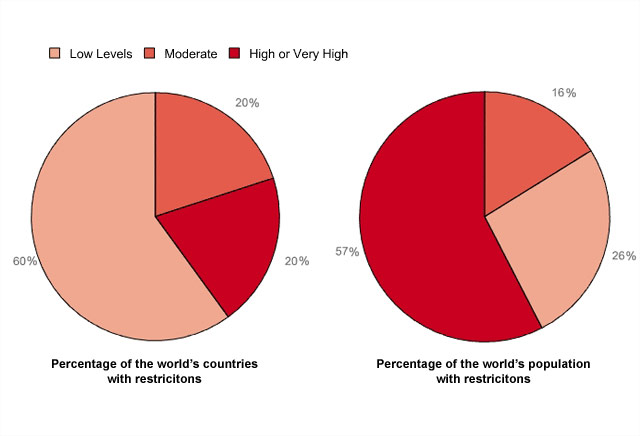Indonesia-2014.com
Oleh Ihsan Ali-Fauzi
12 January 2013
Tidak ada kabar baik menyertai para jamaah Gereja Kristen Indonesia
(GKI) Taman Yasmin di penghujung tahun 2012 yang baru lalu. Seperti
tahun sebelumnya, mereka masih harus merayakan Natal tahun ini di luar
tempat ibadah yang sudah lama mereka idam-idamkan tapi tak kunjung
dapatkan. Itu pun tak selamanya berlangsung dengan aman dan tanpa
ancaman.
Ini satu tantangan kebebasan beragama yang terus menghantui kita di
tahun 2012: ada kelompok tertentu yang tidak bisa menikmati hak untuk
bebas beragama seperti dijanjikan konstitusi, karena pembangunan tempat
ibadah mereka terhalangi. Kontroversi muncul terutama mengenai
pembangunan gereja di tengah-tengah komunitas yang didominasi kaum
Muslim. Tapi kontroversi juga muncul menyangkut pembangunan Masjid Nur
Musofir, misalnya, di Batuplat, Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang
didominasi umat Kristiani.
Ini mencerminkan adanya masalah dalam pengelolaan hubungan yang
harmonis di antara kelompok-kelompok mayoritas dan minoritas agama di
daerah-daerah tertentu. Salah satu sebab mengapa umat Kristiani di NTT
menghalang-halangi pendirian masjid, kata salah satu peneliti yang
sedang mempelajari kasus itu, adalah karena umat Islam melakukan hal
yang sama di Jawa. “Itu seperti balas dendam,” lapornya. Tantangan lainnya, kedua, adalah intensifikasi aksi-aksi kekerasan
yang menyertai konflik-konflik keagamaan. Jika tahun lalu ada tiga
anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang terbunuh dalam peristiwa
anti-JAI di Cikeusik, Banten, kini jumlah korban meninggal lebih banyak.
Akhir Agustus lalu, dua orang meninggal dalam kekerasan anti-Syiah di
Sampang, Madura, Jawa Timur. Lalu, pada akhir Oktober, tiga orang
menjadi korban amuk massa di Bireun, Nanggroe Aceh Darussalam. Yang
sangat mengerikan dan membuat kita bergidik, dua di antaranya dibakar
hidup-hidup!
Dalam kasus-kasus ini, yang menjadi alasan mengapa aksi-aksi
kekerasan, bahkan pembunuhan, dianggap layak dilakukan adalah karena
kelompok mayoritas tertentu merasa bahwa kelompok-kelompok tertentu
menyebarkan kesesatan. Dan di tengah-tengah itu, negara tidak melakukan
apa-apa. Bahkan, di tempat-tempat tertentu, ada indikasi bahwa negara
malah mengkriminalisasi para korban.
Sebagian kalangan – aktivis kebebasan beragama di dalam dan luar
negeri, tapi juga para pengamat dan sarjana – mulai berbicara mengenai
Pakistanisasi Indonesia. Di koran berbahasa Inggris
Jakarta Post,
debat ini sempat melibatkan Duta Besar Pakistan di Indonesia, yang
merasa bahwa penggambaran mengenai negerinya berlebih-lebihan. Ini
merujuk kepada intensifikasi aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok
minoritas, baik dari segi jumlah maupun skala.
Saya tidak akan mendeskripsikan kasus-kasus di atas lebih jauh.
Mereka yang bekerja memonitor naik dan turun kebebasan beragama kita
akan mencatat kasus-kasus ini secara lebih lengkap dan terinci. Di bawah
ini saya ingin mendiskusikan tiga hal yang patut digarisbawahi dari
perkembangan-perkembangan di atas.
Mahalnya Ongkos Kepemimpinan Buruk
Catatan pertama terkait lemahnya kepemimpinan Presiden Soesilo
Bambang Yudhoyono (SBY). Ini bukan masalah kontroversial, karena bahkan
kalangan awam sekalipun sudah banyak bicara mengenainya.
Saya mencatat faktor ini karena dalam perkara jaminan kebebasan
beragama, model kepemimpinannya tidak saja buruk pada dirinya sendiri,
tetapi juga membawa dampak yang jauh lebih buruk pada tingkat-tingkat
kepemimpinan lain di bawahnya. Dalam istilah agama, model kepemimpinan
ini bukan saja sesat (
dhallun) tetapi juga menyesatkan (
mudhillun).
Ini misalnya berbeda dari dampak kepemimpinannya dalam bidang ekonomi:
PDB tetap meningkat dan investasi terus masuk meskipun kepemimpinan SBY
sendiri lemah.
Baru-baru ini (lihat
Jakarta Post, 21 Desember 2012), dampak buruk ini diakui bahkan oleh Wakapolri Nanan Sukarna. Dia dikutip menyatakan:
“We
are conscious of human rights. We have internalized human rights
values. However, we are very much influenced by politics. The country’s
leadership and public policies determine our responses when dealing with
religious conflicts.”
Banyak laporan menyebutkan bahwa aksi-aksi kekerasan atas nama agama
dilakukan dengan legitimasi fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
mengenai aliran-aliran sesat. Penting diingat, fatwa-fatwa ini adalah
hasil Kongres ketujuh MUI (26-29 Juli 2005), yang dibuka SBY. Dalam
pidatonya, SBY menyatakan: “Kami membuka pintu hati, pikiran kami untuk
setiap saat menerima pandangan, rekomendasi dan fatwa dari MUI maupun
dari para ulama, baik langsung kepada saya, kepada saudara Menteri
Agama, atau kepada jajaran pemerintah yang lain. Kami ingin meletakkan
MUI untuk berperan secara sentral yang menyangkut akidah ke-Islaman,
dengan demikian akan jelas bedanya mana-mana yang itu merupakan atau
wilayah pemerintahan kenegaraan, dan mana-mana yang pemerintah atau
negara sepatutnya mendengarkan fatwa dari MUI dan para ulama.”
Pernyataan itu, yang sengaja saya kutip agak panjang dan apa adanya,
menunjukkan betapa SBY seperti sedang cari muka kepada MUI. Ini jelas
harus disayangkan. Selain kepada MUI, dia juga wajib bertanya kepada
lembaga seperti Komnas HAM, yang jelas berwenang menangani masalah
kebebasan beragama.
Banyak catatan menyebutkan, rekor kebebasan beragama kita secara
konsisten memburuk sejak 2008 – dengan skala kekerasan terburuk
berlangsung pada dua tahun terakhir. Di tahun 2013, tahun terakhir
kepresidennya, SBY harus mengambil langkah-langkah tegas untuk
memperbaiki kesalahan-kesalahan kebijakannya di masa lalu.
Ini harus dia lakukan bukan dengan pernyataan penyesalan sesudah
peristiwa kekerasan berlangsung. Melainkan, dia harus memimpin peneguhan
kembali hak-hak kelompok minoritas agama dari berbagai segi.
Di antara aktor-aktor lain di Indonesia, SBY adalah aktor dengan
sumber daya politik paling besar untuk membalikkan situasi di atas. Dia
bisa memobilisasi para pemimpin agama, juga para pemimpin lainnya, untuk
melakukan hal itu. Jika tidak demikian, dia akan dicatat sejarah
republik ini sebagai presiden yang paling buruk rekornya dalam membela
hak-hak kelompok minoritas agama di negeri pluralis ini. Jika
Pakistanisasi Indonesia nanti terbukti, beberapa dekade kemudian, dia
akan dikecam sebagai pionirnya.
Kerukunan versus Kebebasan
Catatan kedua terkait dengan dasar pertimbangan yang sering digunakan
aparat pemerintah dalam menangani konflik-konflik keagamaan. Rekor
kebebasan beragama kita di tahun 2012 ditandai oleh makin dominannya
pendekatan “kerukunan”, dalam persaingannya dengan pendekatan
“kebebasan”, dalam penanganan atas konflik-konflik ini. Pada yang
pertama, tidak penting siapa yang salah atau benar. Yang penting adalah
kembalinya
order, tatanan, meski kedamaian yang tercipta dalam kerukunan yang dipaksakan itu hanya semu.
Inilah yang mendasari mengapa pemerintah memilih opsi relokasi
kelompok Syi`ah menyusul konflik keagamaan di Sampang, Madura. Dengan
begini, memasuki 2013, kita akan dihadapkan pada masalah pengungsi baru
yang kita ciptakan sendiri: ada 63 keluarga di sana, terdiri atas 282
orang, yang jatah makannya sekarang, apalagi nanti, entah siapa yang
tanggung. Padahal kita tahu, di Transito, Mataram, masih ada 115 orang
pengungsi akibat kekerasan anti-JAI pada 2007: terdiri atas 36 keluarga,
di mana tiap keluarga dipisahkan oleh kain atau kerdus bekas seluas 3x2
meter persegi, mereka sulit memeroleh KTP baru, yang belakangan
mempersulit mereka mengurus surat-surat resmi lainnya. Kita seperti
keledai yang tidak bisa mengambil pelajaran dari berlaku bodoh di masa
lalu.
Pendekatan kerukunan umumnya ditempuh aparat pemerintah karena
membela kebebasan, yang biasanya menjadi tuntutan kelompok minoritas,
tidak menguntungkan secara politis. Ini ditunjang oleh tersedianya
aturan mengenai penodaan agama (KUHP Pasal 156a), yang eksistensinya
bahkan diteguhkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010. Dalam politik
elektoral seperti yang berlangsung sekarang, kesempatan ini dimanfaatkan
oleh para politisi untuk menarik dukungan massa dengan meminggirkan
kelompok minoritas agama atau dengan tidak membela mereka ketika konflik
terjadi.
Yang menyedihkan, ini diakui sendiri oleh Mendagri Gamawan Fauzi
dalam pembelaannya terhadap banyak aturan yang bernuansa Syari`ah di
berbagai wilayah di Indonesia. Dan bahkan yang lebih buruk dari itu,
justru aturan mengenai penodaan inilah yang hendak dimajukan Presiden
SBY ke dunia internasional sebagai “sumbangan Indonesia” bagi perdamaian
dunia!
Belajar dari Kasus-kasus “Positif”
Karena alasan-alasan di atas, dapat dipastikan bahwa model pendekatan
kerukunan masih akan mendominasi cara penanganan konflik-konflik
keagamaan di Indonesia di masa depan. Apalagi 2013 adalah tahun
persiapan menjelang pemilihan umum presiden di tahun berikutnya (2014),
di mana para politisi akan memanfaatkan segala cara untuk meraih
dukungan politik.
Yang menarik, dan ini catatan ketiga saya, kasus-kasus seperti
disebutkan di atas tidak umum terjadi di seluruh pelosok negeri ini.
Kasus-kasusnya memang meningkat, dan ini jelas
alarming, tetapi
Indonesia sebagai satu unit dan keseluruhan jelas (masih) bisa
dibedakan dari Pakistan. Tolong saya tidak disalahpahami: saya tidak
sedang merayakan aksi-aksi kekerasan atas nama agama, tetapi sedang
mengajak Anda untuk mengambil pelajaran dari kasus-kasus di mana hal itu
tidak terjadi di cukup banyak tempat di Indonesia. Inilah kasus-kasus
yang saya sebut “positif”.
Misalnya sering dikatakan bahwa posisi MUI begitu berpengaruh,
sehingga efek fatwanya kepada kekerasan harus dinisbatkan kepadanya
juga. Setahu saya, belum ada riset sistematis mengenai hal ini. Saya
sendiri meragukan klaim itu, karena jika demikian, fatwa MUI akan
melahirkan kekerasan di mana-mana. Kenyataannya tidak: sebagian Muslim
Indonesia tidak peduli dengannya, sebagian lainnya bahkan
menertawakannya.
Ada jarak cukup panjang, berisi rangkaian mekanisme dan proses, agar
sebuah fatwa (artinya: opini) tentang sesatnya kelompok tertentu berbuah
menjadi aksi kekerasan atas kelompok itu, oleh orang lain yang
dipengaruhi opini bersangkutan. Selain fatwa penyesatan dari MUI, si
fulan yang
dipengaruhi fatwa itu memerlukan: (a) kemauan untuk melakukan aksi-aksi
kekerasan dengan dukungan fatwa itu, (b) kemampuan untuk melakukannya,
dan (c) kesempatan untuk melakukannya (misalnya, polisi tidak
menghalangi, kalau bukan malah mendukungnya).
Mekanisme dan proses inilah yang harus ditelusuri. Dari riset kami di
PUSAD Paramadina yang masih berlangsung, misalnya, kami menemukan pola
pemolisian yang saling bertentangan terhadap aksi-aksi anti-JAI di
Manislor dan di Cikeusik. Meski sama-sama ditopang sentimen anti-JAI
yang kuat dan sama-sama berlangsung di Jawa Barat, sangat jelas
kelihatan bahwa ketegasan aparat polisi ada di yang pertama dan absen di
yang kedua. Apa sumber ketegasan itu, terlalu panjang diceritakan di
sini. Tapi semuanya bukan mustahil untuk dipelajari dan ditiru di
tempat-tempat lain.
Hal yang sama juga ditemukan jika kita membandingkan bagaimana polisi
menangani aksi-aksi anti-Syi`ah di Sampang, Madura, dan di Bangil,
keduanya di Jawa Timur. Itu akan tampak jika kita menelusuri kapan
konflik bermula dan bereskalasi, apa yang dilakukan para pemimpin –
agama, politik, dan lainnya – di masing-masing tahapan konflik itu, dan
bagaimana aparat polisi memberi reaksi.
Pakistanisasi Indonesia?
Dalam perdebatan mengenai Pakistanisasi Indonesia, Dubes Pakistan
mencela para kritikus Pakistan sebagai sedang menjelek-jelekkan negara
itu. Dari berbagai laporan mengenai apa yang terjadi di negara itu, kita
tahu dia sedang berbohong. Bukankah tugas seorang dubes di negara
tertentu memang berbohong tentang negaranya demi kepentingan negaranya
itu?
Terlepas dari itu, saya sendiri tidak terlalu yakin dengan argumen
Pakistanisasi Indonesia. Pertama, di sini tidak ada Taliban yang di
Pakistan seperti bebas menjalankan aksi-aksi kekerasannya bahkan di
siang bolong. Di Indonesia, aksi-aksi kekerasan atas nama agama masih
kuat dikecam orang dan masih membuat pemerintah malu, meski langkah
lanjutan dari rasa malu atau kecaman itu belum tentu ada atau efektif.
Kedua, beda dari Pakistan yang sejak pertama didirikan atas nama
Islam, Indonesia adalah negara yang sejak lahirnya plural. Dari segi
konstitusi dan elektoral, juga jelas bahwa kaum Muslim Indonesia, dulu
dan sekarang, tidak mendukung Pakistanisasi Indonesia.
Tapi apa yang mustahil terjadi di kolong langit ini? Apalagi jika kita memang membiarkannya terjadi.
Ihsan Ali-Fauzi adalah Direktur Pusat Studi Agama dan demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, dan dosen pada Universitas Paramadina, Jakarta.
Retrieved from:
http://www.indonesia-2014.com/read/2013/01/12/kebebasan-beragama-2013-tiga-catatan#.UPQzqPL4aeZ