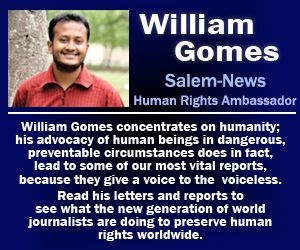Masnun Tahir*
Di penghujung tahun 2007, sejarah hubungan umat beragama masih mencatat adanya gesekan yang berujung kekerasan atas nama agama. Ironisnya, konflik antar agama yang terjadi di negeri ini tidak lagi terjadi antar agama tetapi terjadi intern agama. Salah satu contoh adalah pengusiran dan perusakan rumah tinggal dan tempat ibadah warga Ahmadiyah di Lombok NTB beberapa waktu lalu. Dampak dari kejadian itu, hingga kini masih dirasakan oleh warga yang mengaku “pengikut Mirza Gulam Ahmad” ini.
Ketika saya mengunjungi pengungsian pengikut jamaah Ahmadiyah di Lombok beberapa waktu lalu, perasaan miris muncul saat penuturan jujur keluar dari mulut para jama’ah Ahmadiyah “banyak keluarga kami yang kini terpaksa harus kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian dan semua ketentraman yang kami bangun selama ini. Anak-anak kami kini tak lagi bisa sekolah. Istri-istri kami tak leluasa lagi pergi ke tempat-tempat umum, seperti pasar. Takut dan malu”.
“Mengerikan” pikir saya, agama yang sejatinya diharapkan mampu menjadi pengayom, pemberi rasa aman, penebar kedamaian di bumi, kini justru berubah menjadi api pemantik kebencian dan permusuhan di kalangan penganutnya. Namun mengapa kadang iman gagal mencapai mokhsa di lingkungan pengikutnya? Seperti yang dikatakan Friedrich Nietzsche, salah seorang pembaharu filsafat teologi yang paling terkemuka akhir abad ke sembilanbelas, ia melihat ada realitas yang mengerikan tentang apa yang disebut “agama” pada masanya. Kancah perang dan peran sebagai media untuk saling membenci banyak diprakarsai oleh operasionalisasi agama. Agama tidak hadir sebagai sosok humanis dan menghargai kehidupan manusia. Nietzsche mengambil kesimpulan bahwa kesadaran historis yang plagiatiflah yang tertinggal dalam agama dan diimani jutaan orang. Selebihnya tidak ada. Agama telah berkarat. Gott ist tot, “Tuhan telah mati”, kata-kata yang paling populer darinya ketika memaknai gejala eksploitatif, holocaust, dan misoginis yang diperankan agama.
Kekerasan terhadap Jamaah ini bukan sekali terjadi. Ketika maraknya demo anti Ahmadiyah sekitar Agustus 2005 saya pernah diundang untuk ceramah dalam tablig Akbar di Masjid Jami’ Kabupaten Lombok Tengah oleh panitia yang mengatasnamakan diri AMANAH (Aliansi Masyarakat Anti Ahmadiyah). Dari TOR yang mereka sodorkan, saya memahami bahwa tujuan penyelenggaran tablig itu ialah ajakan untuk merapatkan barisan menghujat Ahmadiyah, tetapi saya menolak hadir dengan memberikan berbagai argumen. Saya mencoba memberikan penjelasan bahwa banyak ayat al-Qur’an yang memberikan kebebasan beragama dan tidak ada jalan pemaksaan apalagi kekerasan dalam Islam, saya juga mencontohkan sikap dua figur ulama kharismatik di Pulau Lombok seperti; al-Magfurlahu TGH. M.Zainuddin Abdul Madjid (Pendiri NW) dan TGH. M.Faisal (Pembawa NU ke Lombok) terhadap jamaah Ahmadiyah ini. Dua tokoh yang sangat dihormati oleh Gus Dur ini sepengetahuan saya belum pernah berfatwa tentang sesatnya Ahmadiyah, apalagi sampai mengajak dan mobilisasi umat untuk menyerang mereka. Hal ini dibuktikan adanya masjid Ahmadiyah di jalan Sudirman Pancor tidak jauh dari kantor sekretariat PBNW, begitu juga di Praya para jamaah panatik TGH. Faisal memberikan kebebasan kepada jama’ah Ahmadiyah untuk menjalankan ibadahnya.
Nasib jamaah Ahmadiyah di Pulau Lombok, mengingatkan saya pada perlakuan masyarakat kepada aliran yang “berlawanan” dengan agama mainstream seperti Islam Wetu Telu. Sekedar informasi tambahan, sebagai kelompok minoritas, keberadaan Islam Wetu Telu ditekan oleh tiga lapis “penindasan” sekaligus, yakni arus modernitas, penetrasi aktif dakwah Islamiyah yang tak kunjung surut, dan implikasi massif dari kebijakan politik khususnya program transmigrasi. Penganut Islam Wetu Telu yang tersisa saat ini semakin terpencil dari komunitas besar etnis Sasak (Islam Wetu Lima) dan distigma sebagai tingkatan masyarakat yang “ketinggalan zaman” dan secara teologis “sesat” dan karenanya perlu diluruskan.
Saya melihat kasus Ahmadiyah ini merupakan masalah pergulatan klaim kebenaran yang biasa terjadi sepanjang sejarah antara kalangan tekstualis, konservatif dan inovatif, arabis dan kultural, dan antar berbagai varian Islam lain. Disinilah sebenarnya kritik wacana agama dan pemahaman yang utuh dan tidak tunggal tentang agama dibutuhkan.
Salah satu ketidaktunggalan dalam pemahaman agama juga diakibatkan oleh perjumpaan (encounter) berbagai macam tradisi kesejarahan agama melalui praktik antar-agama. Di dunia global ini, sesuatu yang tak dapat dibantah adalah penghuni agama akhirnya mencoba merumuskan konsep moralitas baru. Pertama, masalah moral internal suatu agama yang memiliki legitimasi objektif tentang sisi-sisi keyakinan dirinya terkait dengan hal yang tak dapat dihindari sebagai entitas eksklusif. Kedua, rumusan agama-agama mencari kerangka minimal untuk bergerak secara bersama-sama menghadapi tantangan kegelisahan umat masing-masing. Dan ketiga, membiarkan dengan penuh tanggung jawab pada agama agar berada di kolam besar globalisasi berdasarkan sisi kelenturan dan pluralitasnya. Hal ini tentu sebagai cara memproses sebuah pengujian agama historis, yaitu yang dapat menyesuaikan dengan hukum sejarah yang menjamin perbedaan. Dengan demikian kita tidak congkak mengkafirkan atau mengklaim mereka sesat, bisa jadi mereka lebih mulia dan lebih Islam di hadapan Tuhan (kufrun indan nass wa lakin mukmin indallah). Pertanggungjawaban seorang umat kepada Tuhannya tidak dapat dirampas oleh orang lain, disamaratakan, atau diklaim karena tidak ada nilai objektif yang dapat dijadikan parameter. Takaran seseorang makin beriman atau makin kafir terhadap keyakinannya tidak dapat divonis oleh orang lain. Keduanya memiliki karakter yang tidak dapat dipertemukan dalam sebuah ruangan eksekusi.
Saya sangat menyayangkan Fatwa MUI beberapa waktu yang lalu yang menganggap Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan seharusnya kembali kepada kemurnian Islam atau membentuk agama baru. MUI pernah berfatwa dua kali tentang keberadaan Ahmadiyah yaitu tahun 1984 dan tanggal 29 Juli 2005. Inti fatwanya bahwa Ahmadiyah keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan. Fatwa MUI inilah yang dijadikan dalil pembenar bagi sekelompok orang untuk melabelkan sesat dan bahkan mengusir serta membakar rumah dan tempat ibadah mereka. Klaim “sesat” ini lalu berujung pada pengajuan opsi terbatas bagi jemaat Ahmadiyah: menyesuaikan ajarannya dengan keyakinan umum umat Islam atau keluar dari Islam dan membikin agama baru. Ini logika teologis dan solusi klise yang rutin dilansir para ulama, terkhusus mereka yang terhimpun di MUI, dan kemudian dipegangi para pejabat lokal maupun nasional. Padahal bagi saya, nilai kebenaran masing-masing keyakinan sejatinya setara. Oleh karena itu, salah satu keyakinan tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai benar tidaknya keyakinan lain, meski keyakinan pertama ini di anut oleh mayoritas karena apabila dilihat secara epistemologis, suatu keyakinan tak lebih merupakan hasil pemahaman, produk pemikiran yang bersifat ijtihadi, sebuah tafsir terhadap doktrin pokok.
Menyikapi pluralitas keyakinan keagamaan dengan kekerasan seperti pada kasus Ahmadiyah bukan pilihan yang bijaksana, bahkan kontraproduktif dengan pesan dasar Islam sebagai agama penebar kasih dan rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil alamin). Oleh karena itu, jika kita masih memandang keyakinan teologis Ahmadiyah “salah” atau “sesat”, sikap terbaik adalah menjalankan dakwah ke tengah mereka dengan cara-cara tanpa kekerasan, fisik maupun non-fisik. Menyampaikan dakwah dengan hikmah dan kebijakan seperti yang pernah dilakukan Rasulullah ketika berdiskusi dengan orang Kristen dan Nazran mengatakan, “mari kita diskusi, berbincang-bincang siapa tahu ada kebenaran di kami atau di anda”.
Selain itu di dalam al-Qur’an Allah menawarkan setidaknya tiga pilihan metodis dalam mengajak manusia ke jalan kebenaran, yakni (1) menjelaskan al-hikmah; (2) mengetengahkan petunjuk atau nasihat yang baik (al-ma’izah al-hasanah); dan (3) melangsungkan mujadalah (dialog) dengan cara terbaik. Ketiganya harus dijalankan dengan cara–cara simpatik (ahsan), lemah lembut, tanpa memaksa sebagaimana tercermin pada kata “ajaklah” atau “serulah” di awal ayat. Tak ada indikasi implisit atau apalagi eksplisit di ayat tersebut atau ayat-ayat lain, yang menganjurkan cara-cara kekerasan, misalnya paksalah, serbulah, bubarlah, atau bunuhlah. Semoga.
*Dosen IAIN Mataram dan Wakil Katib Syuriah PWNU NTB.
Retrieved from: http://masnuntahir.blogspot.com/2009/05/nasib-ahmadiyah-dan-kritik-wacana-agama.html
Di penghujung tahun 2007, sejarah hubungan umat beragama masih mencatat adanya gesekan yang berujung kekerasan atas nama agama. Ironisnya, konflik antar agama yang terjadi di negeri ini tidak lagi terjadi antar agama tetapi terjadi intern agama. Salah satu contoh adalah pengusiran dan perusakan rumah tinggal dan tempat ibadah warga Ahmadiyah di Lombok NTB beberapa waktu lalu. Dampak dari kejadian itu, hingga kini masih dirasakan oleh warga yang mengaku “pengikut Mirza Gulam Ahmad” ini.
Ketika saya mengunjungi pengungsian pengikut jamaah Ahmadiyah di Lombok beberapa waktu lalu, perasaan miris muncul saat penuturan jujur keluar dari mulut para jama’ah Ahmadiyah “banyak keluarga kami yang kini terpaksa harus kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian dan semua ketentraman yang kami bangun selama ini. Anak-anak kami kini tak lagi bisa sekolah. Istri-istri kami tak leluasa lagi pergi ke tempat-tempat umum, seperti pasar. Takut dan malu”.
“Mengerikan” pikir saya, agama yang sejatinya diharapkan mampu menjadi pengayom, pemberi rasa aman, penebar kedamaian di bumi, kini justru berubah menjadi api pemantik kebencian dan permusuhan di kalangan penganutnya. Namun mengapa kadang iman gagal mencapai mokhsa di lingkungan pengikutnya? Seperti yang dikatakan Friedrich Nietzsche, salah seorang pembaharu filsafat teologi yang paling terkemuka akhir abad ke sembilanbelas, ia melihat ada realitas yang mengerikan tentang apa yang disebut “agama” pada masanya. Kancah perang dan peran sebagai media untuk saling membenci banyak diprakarsai oleh operasionalisasi agama. Agama tidak hadir sebagai sosok humanis dan menghargai kehidupan manusia. Nietzsche mengambil kesimpulan bahwa kesadaran historis yang plagiatiflah yang tertinggal dalam agama dan diimani jutaan orang. Selebihnya tidak ada. Agama telah berkarat. Gott ist tot, “Tuhan telah mati”, kata-kata yang paling populer darinya ketika memaknai gejala eksploitatif, holocaust, dan misoginis yang diperankan agama.
Kekerasan terhadap Jamaah ini bukan sekali terjadi. Ketika maraknya demo anti Ahmadiyah sekitar Agustus 2005 saya pernah diundang untuk ceramah dalam tablig Akbar di Masjid Jami’ Kabupaten Lombok Tengah oleh panitia yang mengatasnamakan diri AMANAH (Aliansi Masyarakat Anti Ahmadiyah). Dari TOR yang mereka sodorkan, saya memahami bahwa tujuan penyelenggaran tablig itu ialah ajakan untuk merapatkan barisan menghujat Ahmadiyah, tetapi saya menolak hadir dengan memberikan berbagai argumen. Saya mencoba memberikan penjelasan bahwa banyak ayat al-Qur’an yang memberikan kebebasan beragama dan tidak ada jalan pemaksaan apalagi kekerasan dalam Islam, saya juga mencontohkan sikap dua figur ulama kharismatik di Pulau Lombok seperti; al-Magfurlahu TGH. M.Zainuddin Abdul Madjid (Pendiri NW) dan TGH. M.Faisal (Pembawa NU ke Lombok) terhadap jamaah Ahmadiyah ini. Dua tokoh yang sangat dihormati oleh Gus Dur ini sepengetahuan saya belum pernah berfatwa tentang sesatnya Ahmadiyah, apalagi sampai mengajak dan mobilisasi umat untuk menyerang mereka. Hal ini dibuktikan adanya masjid Ahmadiyah di jalan Sudirman Pancor tidak jauh dari kantor sekretariat PBNW, begitu juga di Praya para jamaah panatik TGH. Faisal memberikan kebebasan kepada jama’ah Ahmadiyah untuk menjalankan ibadahnya.
Nasib jamaah Ahmadiyah di Pulau Lombok, mengingatkan saya pada perlakuan masyarakat kepada aliran yang “berlawanan” dengan agama mainstream seperti Islam Wetu Telu. Sekedar informasi tambahan, sebagai kelompok minoritas, keberadaan Islam Wetu Telu ditekan oleh tiga lapis “penindasan” sekaligus, yakni arus modernitas, penetrasi aktif dakwah Islamiyah yang tak kunjung surut, dan implikasi massif dari kebijakan politik khususnya program transmigrasi. Penganut Islam Wetu Telu yang tersisa saat ini semakin terpencil dari komunitas besar etnis Sasak (Islam Wetu Lima) dan distigma sebagai tingkatan masyarakat yang “ketinggalan zaman” dan secara teologis “sesat” dan karenanya perlu diluruskan.
Saya melihat kasus Ahmadiyah ini merupakan masalah pergulatan klaim kebenaran yang biasa terjadi sepanjang sejarah antara kalangan tekstualis, konservatif dan inovatif, arabis dan kultural, dan antar berbagai varian Islam lain. Disinilah sebenarnya kritik wacana agama dan pemahaman yang utuh dan tidak tunggal tentang agama dibutuhkan.
Salah satu ketidaktunggalan dalam pemahaman agama juga diakibatkan oleh perjumpaan (encounter) berbagai macam tradisi kesejarahan agama melalui praktik antar-agama. Di dunia global ini, sesuatu yang tak dapat dibantah adalah penghuni agama akhirnya mencoba merumuskan konsep moralitas baru. Pertama, masalah moral internal suatu agama yang memiliki legitimasi objektif tentang sisi-sisi keyakinan dirinya terkait dengan hal yang tak dapat dihindari sebagai entitas eksklusif. Kedua, rumusan agama-agama mencari kerangka minimal untuk bergerak secara bersama-sama menghadapi tantangan kegelisahan umat masing-masing. Dan ketiga, membiarkan dengan penuh tanggung jawab pada agama agar berada di kolam besar globalisasi berdasarkan sisi kelenturan dan pluralitasnya. Hal ini tentu sebagai cara memproses sebuah pengujian agama historis, yaitu yang dapat menyesuaikan dengan hukum sejarah yang menjamin perbedaan. Dengan demikian kita tidak congkak mengkafirkan atau mengklaim mereka sesat, bisa jadi mereka lebih mulia dan lebih Islam di hadapan Tuhan (kufrun indan nass wa lakin mukmin indallah). Pertanggungjawaban seorang umat kepada Tuhannya tidak dapat dirampas oleh orang lain, disamaratakan, atau diklaim karena tidak ada nilai objektif yang dapat dijadikan parameter. Takaran seseorang makin beriman atau makin kafir terhadap keyakinannya tidak dapat divonis oleh orang lain. Keduanya memiliki karakter yang tidak dapat dipertemukan dalam sebuah ruangan eksekusi.
Saya sangat menyayangkan Fatwa MUI beberapa waktu yang lalu yang menganggap Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan seharusnya kembali kepada kemurnian Islam atau membentuk agama baru. MUI pernah berfatwa dua kali tentang keberadaan Ahmadiyah yaitu tahun 1984 dan tanggal 29 Juli 2005. Inti fatwanya bahwa Ahmadiyah keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan. Fatwa MUI inilah yang dijadikan dalil pembenar bagi sekelompok orang untuk melabelkan sesat dan bahkan mengusir serta membakar rumah dan tempat ibadah mereka. Klaim “sesat” ini lalu berujung pada pengajuan opsi terbatas bagi jemaat Ahmadiyah: menyesuaikan ajarannya dengan keyakinan umum umat Islam atau keluar dari Islam dan membikin agama baru. Ini logika teologis dan solusi klise yang rutin dilansir para ulama, terkhusus mereka yang terhimpun di MUI, dan kemudian dipegangi para pejabat lokal maupun nasional. Padahal bagi saya, nilai kebenaran masing-masing keyakinan sejatinya setara. Oleh karena itu, salah satu keyakinan tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai benar tidaknya keyakinan lain, meski keyakinan pertama ini di anut oleh mayoritas karena apabila dilihat secara epistemologis, suatu keyakinan tak lebih merupakan hasil pemahaman, produk pemikiran yang bersifat ijtihadi, sebuah tafsir terhadap doktrin pokok.
Menyikapi pluralitas keyakinan keagamaan dengan kekerasan seperti pada kasus Ahmadiyah bukan pilihan yang bijaksana, bahkan kontraproduktif dengan pesan dasar Islam sebagai agama penebar kasih dan rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil alamin). Oleh karena itu, jika kita masih memandang keyakinan teologis Ahmadiyah “salah” atau “sesat”, sikap terbaik adalah menjalankan dakwah ke tengah mereka dengan cara-cara tanpa kekerasan, fisik maupun non-fisik. Menyampaikan dakwah dengan hikmah dan kebijakan seperti yang pernah dilakukan Rasulullah ketika berdiskusi dengan orang Kristen dan Nazran mengatakan, “mari kita diskusi, berbincang-bincang siapa tahu ada kebenaran di kami atau di anda”.
Selain itu di dalam al-Qur’an Allah menawarkan setidaknya tiga pilihan metodis dalam mengajak manusia ke jalan kebenaran, yakni (1) menjelaskan al-hikmah; (2) mengetengahkan petunjuk atau nasihat yang baik (al-ma’izah al-hasanah); dan (3) melangsungkan mujadalah (dialog) dengan cara terbaik. Ketiganya harus dijalankan dengan cara–cara simpatik (ahsan), lemah lembut, tanpa memaksa sebagaimana tercermin pada kata “ajaklah” atau “serulah” di awal ayat. Tak ada indikasi implisit atau apalagi eksplisit di ayat tersebut atau ayat-ayat lain, yang menganjurkan cara-cara kekerasan, misalnya paksalah, serbulah, bubarlah, atau bunuhlah. Semoga.
*Dosen IAIN Mataram dan Wakil Katib Syuriah PWNU NTB.
Retrieved from: http://masnuntahir.blogspot.com/2009/05/nasib-ahmadiyah-dan-kritik-wacana-agama.html